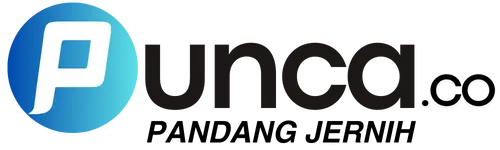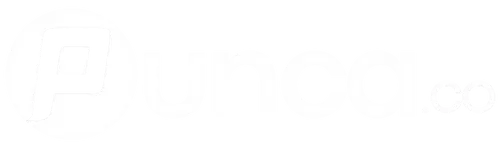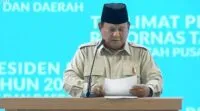“Omon-omon.” Kata-kata itu terlontar dari mulut Presiden Prabowo saat Pilpres 2024, sebagai sindiran kepada calon presiden lainnya yang hingga kini masih mengundang gelak tawa publik.
Dua dekade pasca-penandatanganan MoU Helsinki, Aceh kerap dirayakan sebagai kisah sukses perdamaian di Indonesia. Senjata telah dibungkam, pasukan ditarik, dan Partai Aceh berdiri sebagai simbol transformasi dari gerakan bersenjata ke kancah politik legal. Namun, ketika euforia mereda dan debu pertempuran mengendap, satu pertanyaan tetap menggantung, benarkah kita telah berdamai secara utuh?
Dalam literatur perdamaian, reintegrasi bukan hanya tentang membagikan dana kompensasi atau memberikan pelatihan kerja kepada mantan kombatan. Ia adalah proses panjang, yang menuntut pemulihan martabat, pemenuhan hak, dan pengakuan atas luka kolektif. Sayangnya, di Aceh, reintegrasi pasca-konflik seringkali terjebak dalam pendekatan teknokratis dan transaksional. Dana digelontorkan, rumah dibangun, pelatihan digelar, tapi tanpa keberpihakan serius pada keadilan dan penyembuhan luka sejarah.
Baca juga: Catatan Era Prabowo; Amnesti untuk Koruptor
Mungkin lebih dari ribuan mantan kombatan telah menerima bantuan, namun jumlah itu hanya sebagian kecil dari mereka yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, korban pelanggaran HAM berat, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, hanya mendapat pengakuan simbolik dalam retorika “damai”.
Aceh memang memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sendiri, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Namun, KKR Aceh mandul tanpa dukungan negara. Rekomendasi-rekomendasi KKR hanya menjadi dokumen hening di meja birokrasi. Tidak ada pelaku yang diadili dan tidak ada kompensasi yang layak.
Padahal, tanpa keadilan, tidak akan ada perdamaian yang sejati. John Paul Lederach pernah menyatakan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan kekerasan, tapi hadirnya hubungan yang adil. Dalam konteks Aceh, hubungan itu masih timpang, baik antara masyarakat dan negara, maupun antara korban dan para pelaku kekerasan masa lalu.
Damai seolah telah diarsipkan dalam MoU, dalam qanun, dan dalam narasi-narasi resmi. Tapi di akar rumput, luka belum dijahit, suara korban belum didengar, dan hak-hak dasar belum terpenuhi. Reintegrasi tanpa rekonsiliasi hanya akan melahirkan ketegangan baru yang lebih sunyi, namun tidak kalah mengancam.
Jika kita tidak mulai menempatkan kebenaran, pengakuan, dan keadilan sebagai bagian integral dari reintegrasi, maka Aceh akan tetap menjadi “daerah damai” yang penuh trauma. Ia akan menjadi “laboratorium perdamaian palsu”, tempat di mana konflik berhenti, tapi tidak pernah benar-benar selesai.
Prabowo Subianto paham betul soal konflik. Ia pernah berdiri di medan perang, pernah pula mendengar isak tangis korban dari dekat. Maka, kami percaya, jika ada Presiden yang mampu menyempurnakan damai Aceh, ia salah satunya. Kalau tidak, semua ini hanya akan jadi, meminjam kata beliau sendiri, “omon-omon”.
Penulis : Teuku Yumma Hardika, S.IP / Putra Alm. Abu Arafah, Panglima GAM Meureuhom Daya